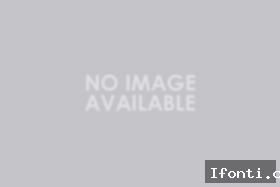Otonomi daerah, sebagai salah satu pilar utama hasil Reformasi 1998, dirancang untuk menjadi instrumen krusial dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, menguatkan fondasi demokrasi lokal, dan mendorong terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh penjuru negeri. Kini, setelah 25 tahun implementasi, daerah-daerah diharapkan telah mencapai kemandirian fiskal. Namun, realitasnya, banyak wilayah masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer dari pusat, sebuah ironi yang terus membayangi cita-cita desentralisasi.
Ketergantungan ini terkuak jelas dari data APBD 2023 yang dirilis Kemendagri, menunjukkan sejumlah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah 30%. Angka-angka ini mencengangkan: Papua Barat hanya 6,15%, Maluku 16,03%, Aceh 16,93%, Sulawesi Barat 18,87%, Maluku Utara 19,79%, Gorontalo 21,16%, Sulawesi Tengah 26,59%, Sulawesi Tenggara 27,89%, dan Bangka Belitung 29,18%. Data ini secara gamblang memperlihatkan betapa jauhnya beberapa daerah dari target kemandirian fiskal yang diharapkan.
Selain tantangan kemandirian fiskal, era otonomi daerah juga masih dihadapkan pada masalah klasik yang menggerogoti, yakni korupsi yang masih merajalela. Di samping itu, rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menjadi pekerjaan rumah besar. Pada tahun 2023, Indonesia terperosok di peringkat 113 dari 193 negara, tertinggal jauh dari negara-negara tetangga ASEAN seperti Thailand (peringkat 76) dan Malaysia (67). Bahkan, indikator angka harapan hidup di Indonesia berada di posisi ketiga terbawah di ASEAN, hanya sedikit di atas Myanmar dan Timor Leste.
Performa Indonesia juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Proyeksi tahun 2025 menempatkan Indonesia di peringkat 77 dengan skor 66,3. Angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura (peringkat 69) dan Vietnam (61) di kawasan ASEAN, serta negara-negara BRICS dan G20 seperti Brasil (54) dan Tiongkok (49). Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan pembangunan di tingkat daerah.
Berbagai ketertinggalan dalam indeks-indeks makro tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa implementasi otonomi daerah belum berjalan optimal, serta tata kelola kepemerintahan yang belum efisien. Ini termasuk pula penggunaan dan pemanfaatan APBD yang kurang efektif, serta pembagian urusan yang kerap kali masih belum sepenuhnya jelas antara pusat dan daerah.
Baca juga:
- Indef: Otonomi Daerah Membuat Ketimpangan Ekonomi Semakin Lebar
- Setara Institute Kritik Wacana Gelar Pahlawan Soeharto: Langgar Amanat Reformasi
- Menjawab Tuntutan Reformasi Polri
Berbagai indikator makro yang disebutkan di atas mencerminkan belum optimalnya kinerja pemerintahan secara keseluruhan, yang sebagian besar merupakan akumulasi dari kinerja pemerintah daerah. Di tengah tuntutan inovasi pelayanan publik yang semakin mendesak di era digital saat ini, ironisnya kita dihadapkan pada realitas yang kontraproduktif. Pada tahun 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyoroti sekitar 24.000 aplikasi milik pemerintah yang dianggap sebagai pemborosan anggaran karena memiliki peran dan fungsi yang hampir serupa.
Dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan, banyaknya aplikasi yang bahkan berasal dari satu pemerintah daerah yang sama, justru tidak mempermudah layanan, melainkan cenderung menyulitkan. Warga direpotkan dengan kewajiban mengunduh dan mengakses berbagai aplikasi, yang pada akhirnya membuat banyak dari mereka enggan berurusan dengan layanan pemerintah kecuali dalam kondisi sangat terpaksa.
Permasalahan serupa juga terjadi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan segala polemik zonasinya, serta keluhan masyarakat terkait masifnya jalan rusak di berbagai daerah. Sektor pendidikan dan pekerjaan umum (perbaikan jalan) merupakan contoh urusan konkuren wajib pelayanan dasar yang didelegasikan kepada daerah. Namun, hingga kini, pembagian urusan konkuren ini masih menjadi problematika klise yang menyebabkan tarik-ulur tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kasus zonasi sekolah merupakan ilustrasi nyata dari ketidaktepatan pembagian urusan konkuren di setiap level pemerintahan yang patut dievaluasi. Lambatnya respons pihak sekolah menengah atas terhadap protes orang tua siswa seringkali terjadi karena kebijakan berada di level provinsi, menciptakan rentang kendali yang cukup jauh dari wilayah kabupaten/kota yang merasakan dampaknya langsung.
Demikian pula, lambatnya respons pemerintah dalam menangani masalah jalan rusak seringkali disebabkan oleh abu-abunya pembagian urusan konkuren. Situasi ini acap kali berujung pada praktik “saling lempar tanggung jawab” antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat, pada akhirnya, tidak peduli siapa yang bertanggung jawab; mereka hanya menginginkan jalan segera diperbaiki demi kelancaran konektivitas dan mobilitas harian.
Polemik mengenai gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah juga tidak kalah pelik. Masalah ini utamanya dipicu oleh pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang berdampak signifikan pada ruang fiskal daerah (DAU). Akibatnya, beberapa daerah terpaksa memangkas tunjangan kinerja atau bahkan menunda pembayaran gaji.
Menyikapi kondisi ini, beberapa kepala daerah mengusulkan agar gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) di pemerintah daerah dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat. Usulan ini sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi melalui sistem penggajian tunggal ASN (single salary system) yang telah diamanahkan oleh UU ASN dan RPJPN 2025-2045 namun belum terealisasi sejak tahun 2014. Kondisi ini berpotensi menjadi “bom waktu” yang dapat mengganggu kinerja aparatur dan berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik.
Langkah ke Depan
Mengutip begawan manajemen Peter Drucker (1994), “sesungguhnya tak ada negara/daerah yang miskin, kecuali yang tak terurus/terkelola.” Dengan melimpahnya sumber daya yang dimiliki negeri ini, seharusnya otonomi daerah dapat menjadi lokomotif utama untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui otonomi daerah, setiap wilayah diberikan keleluasaan untuk berinovasi dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin memudahkan masyarakat.
Mengingat otonomi daerah memang belum sempurna, maka ke depan kebijakan ini perlu terus diperkuat dan disempurnakan. Pertama, transfer urusan dari pemerintah pusat ke daerah hendaknya tidak lagi bersifat simetris. Pendekatan yang lebih tepat adalah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah secara asimetris, sekaligus memberikan ruang afirmasi bagi daerah yang membutuhkan perhatian khusus sesuai karakteristiknya.
Artinya, tidak ada lagi kebijakan “sapu jagat” atau one size fits all. Dengan reformulasi berbasis kapasitas, daerah yang memiliki kemampuan tinggi dapat diberikan kewenangan yang lebih luas, bahkan secara selektif mungkin sebagian urusan absolut. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas terbatas akan difokuskan pada urusan dasar dengan dukungan intensif dari pemerintah pusat.
Kedua, untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat berjalan optimal di daerah, perangkat dekonsentrasi harus diperkuat. Ini penting agar tidak ada lagi praktik saling lempar tanggung jawab dan kewenangan yang merugikan masyarakat.
Ketiga, di era digital yang serbacepat ini, perlu ada reformulasi otonomi daerah untuk mengakhiri duplikasi dan pemborosan anggaran dalam pelayanan publik. Solusinya adalah mengintegrasikan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) ke dalam satu platform tunggal, berbentuk super apps dan one stop service. Replikasi SIPP terbaik dari suatu daerah untuk dimanfaatkan di daerah lain juga bisa menjadi opsi efisien.
Keempat, penguatan peran pemerintah provinsi sebagai “wakil” pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, posisi pemerintah provinsi seringkali ambigu. Reformulasi perlu memperjelas peran provinsi sebagai koordinator lintas wilayah kabupaten/kota, terutama dalam menangani urusan yang bersifat regional (antarwilayah) seperti transportasi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.
Pada intinya, otonomi daerah adalah instrumen vital yang memprioritaskan demokrasi, penyediaan layanan publik jangka panjang, pembangunan sosial ekonomi, perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta kerja sama dengan berbagai aktor pembangunan. Oleh karena itu, penyampaian layanan publik (public service delivery) melalui pembagian urusan pemerintahan konkuren perlu dipertajam. Langkah ini krusial untuk mengoptimalkan efektivitas belanja pemerintah, meningkatkan standar layanan publik, efektivitas operasional pemerintahan, dan keberhasilan setiap kebijakan publik yang dipilih serta dilaksanakan.
Kebijakan otonomi daerah di Indonesia harus terus disempurnakan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi substansial. Dengan demikian, kita dapat menjamin terciptanya kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, siap menghadapi tantangan bonus demografi 2030, dan mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.